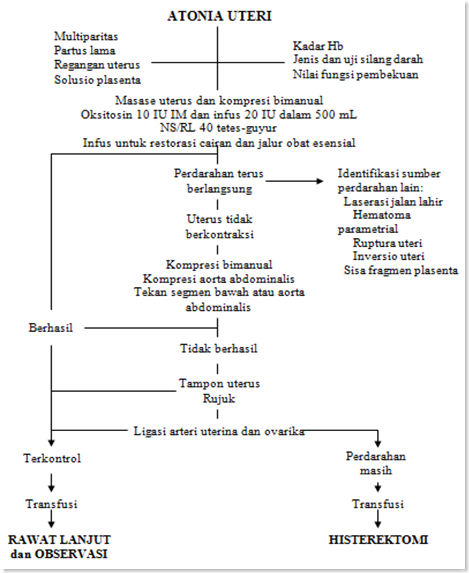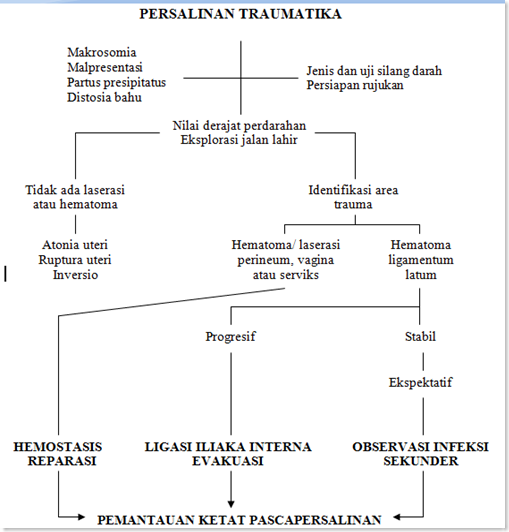Syok bukanlah merupakan suatu diagnosis. Syok merupakan sindrom klinis yang kompleks yang mencakup sekelompok keadaan dengan manifestasi hemodinamik yang bervariasi tetapi petunjuk yang umum adalah tidak memadainya perfusi jaringan.1
Setiap keadaan yang mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan oksigen jaringan, baik karena suplainya yang kurang atau kebutuhannya yang meningkat, menimbulkan tanda-tanda syok.2
Diagnosa adanya syok harus didasarkan pada data-data baik klinis maupun laboratorium yang jelas yang merupakan akibat dari berkurangnya perfusi jaringan. Syok mempengaruhi kerja organ-organ vital dan penangannya memerlukan pemahanam tentang patofisiologi syok.3
Syok bersifat progresif dan terus memburuk. Lingkaran setan dari kemunduran yang progresif akan mengakibatkan syok jika tidak ditangani segera mungkin.1
Syok neurogenik sebenarnya jarang terjadi. Pada syok neurogenik terdapat penurunan tekanan darah sistemik sebagai akibat terjadinya vasodilatasi perifer dan penurunan curah jantung. Vasodilatasi tersebut terjadi karena menurunnya resistensi perifer yang disebabkan oleh gangguan saraf otonom sedangkan penurunan curah jantung disebabkan oleh bertambahnya pengaruh nervus vagus pada jantung sehingga terjadi bradikardi. 4,5
A. Definisi
Syok (renjatan) adalah kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh karena gangguan perfusi jaringan yaitu aliran darah ke organ tubuh tidak dapat mencukupi kebutuhannya.2
Syok sirkulasi dianggap sebagai rangsang paling hebat dari hipofisis adrenalis sehingga menimbulkan akibat fisiologi dan metabolisme yang besar. Syok didefinisikan juga sebagai volume darah sirkulasi tidak adekuat yang mengurangi perfusi, pertama pada jaringan non vital (kulit, jaringan ikat, tulang, otot) dan kemudian ke organ vital (otak, jantung, paru-paru, dan ginjal).1
Syok atau renjatan merupakan suatu keadaan patofisiologis dinamik yang mengakibatkan hipoksia jaringan dan sel.5
Syok juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengancam jiwa yang diakibatkan karena tubuh tidak mendapatkan suplai darah yang adekuat yang mengakibatkan kerusakan pada multiorgan jika tidak ditangani segera dan dapat memburuk dengan cepat.6
B. Klasifikasi
Syok secara umum dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori etiologi yaitu : 1,2,4,7,8,9
1. Syok Hipovolemik
Syok yang disebabkan karena tubuh :
- Kehilangan darah/syok hemoragik
· Hemoragik eksternal : trauma, perdarahan gastrointestinal
· Hemoragik internal : hematoma, hematotoraks
- Kehilangan plasma : luka bakar
- Kehilangan cairan dan elektrolit
· Eksternal : muntah, diare, keringat yang berlebih
· Internal : asites, obstruksi usus
2. Syok Kardiogenik
Gangguan perfusi jaringan yang disebabkan karena disfungsi jantung misalnya : aritmia, AMI (Infark Miokard Akut).
3. Syok Distributif
- Syok Septik
Syok yang terjadi karena penyebaran atau invasi kuman dan toksinnya didalam tubuh yang berakibat vasodilatasi.
- Syok Anafilaktif
Gangguan perfusi jaringan akibat adanya reaksi antigen antibodi yang mengeluarkan histamine dengan akibat peningkatan permeabilitas membran kapiler dan terjadi dilatasi arteriola sehingga venous return menurun.
Misalnya : reaksi tranfusi, sengatan serangga, gigitan ular berbisa
- Syok Neurogenik
Pada syok neurogenik terjadi gangguan perfusi jaringan yang disebabkan karena disfungsi sistim saraf simpatis sehingga terjadi vasodilatasi.
Misalnya : trauma pada tulang belakang, spinal syok
4. Syok Obtruktif
Ketidakmampuan ventrikel untuk mengisi selama diastol sehingga secara nyata menurunkan volume sekuncup dan endnya curah jantung
Misalnya : tamponade kordis, koarktasio aorta, emboli paru, hipertensi pulmoner primer.
C. Patofisiologi
Syok menunjukkan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Hasil akhirnya berupa lemahnya aliran darah yang merupakan petunjuk yang umum, walaupun ada bermacam-macam penyebab. Syok dihasilkan oleh disfungsi empat sistem yang terpisah namun saling berkaitan yaitu ; jantung, volume darah, resistensi arteriol (beban akhir), dan kapasitas vena. Jika salah satu faktor ini kacau dan faktor lain tidak dapat melakukan kompensasi maka akan terjadi syok. Awalnya tekanan darah arteri mungkin normal sebagai kompensasi peningkatan isi sekuncup dan curah jantung. Jika syok berlanjut, curah jantung menurun dan vasokontriksi perifer meningkat. 4, 6
Menurut patofisiologinya, syok terbagi atas 3 fase yaitu : 5,10
1. Fase Kompensasi
Penurunan curah jantung (cardiac output) terjadi sedemikian rupa sehingga timbul gangguan perfusi jaringan tapi belum cukup untuk menimbulkan gangguan seluler. Mekanisme kompensasi dilakukan melalui vasokonstriksi untuk menaikkan aliran darah ke jantung, otak dan otot skelet dan penurunan aliran darah ke tempat yang kurang vital. Faktor humoral dilepaskan untuk menimbulkan vasokonstriksi dan menaikkan volume darah dengan konservasi air. Ventilasi meningkat untuk mengatasi adanya penurunan kadar oksigen di daerah arteri. Jadi pada fase kompensasi ini terjadi peningkatan detak dan kontraktilitas otot jantung untuk menaikkan curah jantung dan peningkatan respirasi untuk memperbaiki ventilasi alveolar. Walau aliran darah ke ginjal menurun, tetapi karena ginjal mempunyai cara regulasi sendiri untuk mempertahankan filtrasi glomeruler. Akan tetapi jika tekanan darah menurun, maka filtrasi glomeruler juga menurun.
2. Fase Progresif
Terjadi jika tekanan darah arteri tidak lagi mampu mengkompensasi kebutuhan tubuh. Faktor utama yang berperan adalah jantung. Curah jantung tidak lagi mencukupi sehingga terjadi gangguan seluler di seluruh tubuh. Pada saat tekanan darah arteri menurun, aliran darah menurun, hipoksia jaringan bertambah nyata, gangguan seluler, metabolisme terganggu, produk metabolisme menumpuk, dan akhirnya terjadi kematian sel.
Dinding pembuluh darah menjadi lemah, tak mampu berkonstriksi sehingga terjadi bendungan vena, vena balik (venous return) menurun. Relaksasi sfinkter prekapiler diikuti dengan aliran darah ke jaringan tetapi tidak dapat kembali ke jantung. Peristiwa ini dapat menyebabkan trombosis kecil-kecil sehingga dapat terjadi koagulopati intravasa yang luas (DIC = Disseminated Intravascular Coagulation).
Menurunnya aliran darah ke otak menyebabkan kerusakan pusat vasomotor dan respirasi di otak. Keadaan ini menambah hipoksia jaringan. Hipoksia dan anoksia menyebabkan terlepasnya toksin dan bahan lainnya dari jaringan (histamin dan bradikinin) yang ikut memperjelek syok (vasodilatasi dan memperlemah fungsi jantung). Iskemia dan anoksia usus menimbulkan penurunan integritas mukosa usus, pelepasan toksin dan invasi bakteri usus ke sirkulasi.
Invasi bakteri dan penurunan fungsi detoksikasi hepar memperjelek keadaan. Dapat timbul sepsis, DIC bertambah nyata, integritas sistim retikuloendotelial rusak, integritas mikro sirkulasi juga rusak. Hipoksia jaringan juga menyebabkan perubahan metabolisme dari aerobik menjadi anaerobik. Akibatnya terjadi asidosis metabolik, terjadi peningkatan asam laktat ekstraseluler dan timbunan asam karbonat di jaringan.
3. Fase Irrevesibel/Refrakter
Karena kerusakan seluler dan sirkulasi sedemikian luas sehingga tidak dapat diperbaiki. Kekurangan oksigen mempercepat timbulnya ireversibilitas syok. Gagal sistem kardiorespirasi, jantung tidak mampu lagi memompa darah yang cukup, paru menjadi kaku, timbul edema interstisial, daya respirasi menurun, dan akhirnya anoksia dan hiperkapnea.
D. Manifestasi Klinis
Manifestasi klinis tergantung pada penyebab syok (kecuali syok neurogenik) yang meliputi : 2, 6,10,11
1. Sistem pernafasan : nafas cepat dan dangkal
2. Sistem sirkulasi : ekstremitas pucat, dingin, dan berkeringat dingin, na-
di cepat dan lemah, tekanan darah turun bila kehilangan darah menca-
pai 30%.
3. Sistem saraf pusat : keadaan mental atau kesadaran penderita bervariasi tergantung derajat syok, dimulai dari gelisah, bingung sampai keadaan tidak sadar.
4. Sistem pencernaan : mual, muntah
5. Sistem ginjal : produksi urin menurun (Normalnya 1/2-1 cc/kgBB/jam)
6. Sistem kulit/otot : turgor menurun, mata cekung, mukosa lidah kering.
7. Individu dengan syok neurogenik akan memperlihatkan kecepatan denyut jantung yang normal atau melambat, tetapi akan hangat dan kering apabila kulitnya diraba.
E. Derajat Syok
Menentukan derajat syok :4
1. Syok Ringan
Penurunan perfusi hanya pada jaringan dan organ non vital seperti kulit, lemak, otot rangka, dan tulang. Jaringan ini relatif dapat hidup lebih lama dengan perfusi rendah, tanpa adanya perubahan jaringan yang menetap (irreversible). Kesadaran tidak terganggu, produksi urin normal atau hanya sedikit menurun, asidosis metabolik tidak ada atau ringan.
2. Syok Sedang
Perfusi ke organ vital selain jantung dan otak menurun (hati, usus, ginjal). Organ-organ ini tidak dapat mentoleransi hipoperfusi lebih lama seperti pada lemak, kulit dan otot. Pada keadaan ini terdapat oliguri (urin kurang dari 0,5 mg/kg/jam) dan asidosis metabolik. Akan tetapi kesadaran relatif masih baik.
3. Syok Berat
Perfusi ke jantung dan otak tidak adekuat. Mekanisme kompensasi syok beraksi untuk menyediakan aliran darah ke dua organ vital. Pada syok lanjut terjadi vasokontriksi di semua pembuluh darah lain. Terjadi oliguri dan asidosis berat, gangguan kesadaran dan tanda-tanda hipoksia jantung (EKG abnormal, curah jantung menurun).
F. Pemeriksaan1,6,9,11, 12
1. Anamnesis
Pada anamnesis, pasien mungkin tidak bisa diwawancara sehingga riwayat sakit mungkin hanya didapatkan dari keluarga, teman dekat atau orang yang mengetahui kejadiannya, cari :
- Riwayat trauma (banyak perdarahan atau perdarahan dalam perut)
- Riwayat penyakit jantung (sesak nafas)
- Riwayat infeksi (suhu tinggi)
- Riwayat pemakaian obat ( kesadaran menurun setelah memakan obat).
2. Pemeriksaan fisik
- Kulit
Suhu raba dingin (hangat pada syok septik hanya bersifat sementara, karena begitu syok berlanjut terjadi hipovolemia)
Warna pucat (kemerahan pada syok septik, sianosis pada syok kardiogenik dan syok hemoragi terminal)
Basah pada fase lanjut syok (sering kering pada syok septik).
- Tekanan darah
Hipotensi dengan tekanan sistolik < 80 mmHg (lebih tinggi pada penderita yang sebelumnya mengidap hipertensi, normal atau meninggi pada awal syok septik)
- Status jantung
Takikardi, pulsus lemah dan sulit diraba.
- Status respirasi
Respirasi meningkat, dan dangkal (pada fase kompensasi) kemudian menjadi lambat (pada syok septik, respirasi meningkat jika kondisi memburuk)
- Status Mental
Gelisah, cemas, agitasi, tampak ketakutan. Kesadaran dan orientasi menurun, sopor sampai koma.
- Fungsi Ginjal
Oliguria, anuria (curah urin < 30 ml/jam, kritis)
- Fungsi Metabolik
Asidosis akibat timbunan asam laktat di jaringan (pada awal syok septik dijumpai alkalosis metabolik, kausanya tidak diketahui). Alkalosis respirasi akibat takipnea
- Sirkulasi
Tekanan vena sentral menurun pada syok hipovolemik, meninggi pada syok kardiogenik
- Keseimbangan Asam Basa
Pada awal syok pO2 dan pCO2 menurun (penurunan pCO2 karena takipnea, penurunan pO2 karena adanya aliran pintas di paru).
3. Pemeriksaan Penunjang
- Darah (Hb, Hmt, leukosit, golongan darah), kadar elektrolit, kadar ureum, kreatinin, glukosa darah.
- Analisa gas darah
- EKG
G. Diagnosis
Kriteria diagnosis :13
1. Penurunan tekanan darah sistolik > 30 mmHg
2. Tanda perfusi jaringan kurang
3. Takikardi, pulsus lemah
H. Diagnosis Banding13
1. Semua jenis syok.
2. Sinkope (pingsan)
3. Histeria
I. Komplikasi6,10,11
1. Kegagalan multi organ akibat penurunan aliran darah dan hipoksia jaringan yang berkepanjangan.
2. Sindrom distress pernapasan dewasa akibat destruksi pertemuan alveolus kapiler karena hipoksia
3. DIC (Koagulasi intravascular diseminata) akibat hipoksia dan kematian jaringan yang luas sehingga terjadi pengaktifan berlebihan jenjang koagulasi.
J. Penatalaksanaan2,12,13
Penanggulangan syok dimulai dengan tindakan umum yang bertujuan untuk memperbaiki perfusi jaringan; memperbaiki oksigenasi tubuh; dan mempertahankan suhu tubuh. Tindakan ini tidak bergantung pada penyebab syok. Diagnosis harus segera ditegakkan sehingga dapat diberikan pengobatan kausal. Segera berikan pertolongan pertama sesuai dengan prinsip resusitasi ABC. Jalan nafas (A = air way) harus bebas kalau perlu dengan pemasangan pipa endotrakeal. Pernafasan (B = breathing) harus terjamin, kalau perlu dengan memberikan ventilasi buatan dan pemberian oksigen 100%. Defisit volume peredaran darah (C = circulation) pada syok hipovolemik sejati atau hipovolemia relatif (syok septik, syok neurogenik, dan syok anafilaktik) harus diatasi dengan pemberian cairan intravena dan bila perlu pemberian obat-obatan inotropik untuk mempertahankan fungsi jantung atau obat vasokonstriktor untuk mengatasi vasodilatasi perifer. Segera menghentikan perdarahan yang terlihat dan mengatasi nyeri yang hebat, yang juga bisa merupakan penyebab syok. Pada syok septik, sumber sepsis harus dicari dan ditanggulangi.
Penanganannya meliputi:
1. Umum :
Memperbaiki sistim pernafasan :
- Bebaskan jalan nafas
- Terapi oksigen
- Bantuan nafas
Memperbaiki sistim sirkulasi:
- Pemberian cairan
- Hentikan perdarahan yang terjadi
- Monitor nadi, tekanan darah, perfusi perifer, produksi urin
Menghilangkan atau mengatasi penyebab syok.
2. Khusus :
Obat farmakologik :
- Tergantung penyebab syok
- Vasopresor (kontraindikasi syok hipovolemik)
- Vasodilator
SYOK NEUROGENIK
A. Definisi
Syok neurogenik merupakan kegagalan pusat vasomotor sehingga terjadi hipotensi dan penimbunan darah pada pembuluh tampung (capacitance vessels).3
Syok neurogenik terjadi karena hilangnya tonus pembuluh darah secara mendadak di seluruh tubuh.10
Syok neurogenik juga dikenal sebagai syok spinal. Bentuk dari syok distributif, hasil dari perubahan resistensi pembuluh darah sistemik yang diakibatkan oleh cidera pada sistem saraf (seperti: trauma kepala, cidera spinal, atau anestesi umum yang dalam).10,14
B. Etiologi
Penyebabnya antara lain : 3,4,5
1. Trauma medula spinalis dengan quadriplegia atau paraplegia (syok spinal).
2. Rangsangan hebat yang kurang menyenangkan seperti rasa nyeri hebat pada fraktur tulang.
3. Rangsangan pada medula spinalis seperti penggunaan obat anestesi spinal/lumbal.
4. Trauma kepala (terdapat gangguan pada pusat otonom).
5. Suhu lingkungan yang panas, terkejut, takut.
C. Patofisiologi
Syok neurogenik termasuk syok distributif dimana penurunan perfusi jaringan dalam syok distributif merupakan hasil utama dari hipotensi arterial karena penurunan resistensi pembuluh darah sistemik (systemic vascular resistance). Sebagai tambahan, penurunan dalam efektifitas sirkulasi volume plasma sering terjadi dari penurunan venous tone, pengumpulan darah di pembuluh darah vena, kehilangan volume intravaskuler dan intersisial karena peningkatan permeabilitas kapiler. Akhirnya, terjadi disfungsi miokard primer yang bermanifestasi sebagai dilatasi ventrikel, penurunan fraksi ejeksi, dan penurunan kurva fungsi ventrikel.11,16
Pada keadaan ini akan terdapat peningkatan aliran vaskuler dengan akibat sekunder terjadi berkurangnya cairan dalam sirkulasi. Syok neurogenik mengacu pada hilangnya tonus simpatik (cedera spinal). Gambaran klasik pada syok neurogenik adalah hipotensi tanpa takikardi atau vasokonstriksi kulit.15
Syok neurogenik terjadi karena reaksi vasovagal berlebihan yang mengakibatkan vasodilatasi menyeluruh di regio splanknikus, sehingga perfusi ke otak berkurang. Reaksi vasovagal umumnya disebabkan oleh suhu lingkungan yang panas, terkejut, takut atau nyeri. Syok neurogenik bisa juga akibat rangsangan parasimpatis ke jantung yang memperlambat kecepatan denyut jantung dan menurunkan rangsangan simpatis ke pembuluh darah. Misalnya pingsan mendadak akibat gangguan emosional.5,10
Pada penggunaan anestesi spinal, obat anestesi melumpuhkan kendali neurogenik sfingter prekapiler dan menekan tonus venomotor. Pasien dengan nyeri hebat, stress, emosi dan ketakutan meningkatkan vasodilatasi karena mekanisme reflek yang tidak jelas yang menimbulkan volume sirkulasi yang tidak efektif dan terjadi sinkop.9
D. Manifestasi Klinis
Hampir sama dengan syok pada umumnya tetapi pada syok neurogenik terdapat tanda tekanan darah turun, nadi tidak bertambah cepat, bahkan dapat lebih lambat (bradikardi) kadang disertai dengan adanya defisit neurologis berupa quadriplegia atau paraplegia . Sedangkan pada keadaan lanjut, sesudah pasien menjadi tidak sadar, barulah nadi bertambah cepat. Karena terjadinya pengumpulan darah di dalam arteriol, kapiler dan vena, maka kulit terasa agak hangat dan cepat berwarna kemerahan.3,4,14,15
E. Diagnosis
Hampir sama dengan syok pada umumnya tetapi pada syok neurogenik terdapat tanda tekanan darah turun, nadi tidak bertambah cepat, bahkan dapat lebih lambat (bradikardi) kadang disertai dengan adanya defisit neurologis berupa quadriplegia atau paraplegia. 3,4,14,15
F. Diagnosis Banding
Diagnosis banding syok neurogenik adalah sinkop vasovagal. Keduanya sama-sama menyebabkan hipotensi karena kegagalan pusat pengaturan vasomotor tetapi pada sinkop vasovagal hal ini tidak sampai menyebabkan iskemia jaringan menyeluruh dan menimbulkan gejala syok.1,9 Diagnosis banding yang lain adalah syok distributif yang lain seperti syok septik, syok anafilaksi. Untuk syok yang lain biasanya sulit dibedakan tetapi anamnesis yang cermat dapat membantu menegakkan diagnosis.2,4,7,8
G. Penatalaksanaan
Konsep dasar untuk syok distributif adalah dengan pemberian vasoaktif seperti fenilefrin dan efedrin, untuk mengurangi daerah vaskuler dengan penyempitan sfingter prekapiler dan vena kapasitan untuk mendorong keluar darah yang berkumpul ditempat tersebut. 4,9
1. Baringkan pasien dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki (posisi Trendelenburg).
2. Pertahankan jalan nafas dengan memberikan oksigen, sebaiknya dengan menggunakan masker. Pada pasien dengan distress respirasi dan hipotensi yang berat, penggunaan endotracheal tube dan ventilator mekanik sangat dianjurkan. Langkah ini untuk menghindari pemasangan endotracheal yang darurat jika terjadi distres respirasi yang berulang. Ventilator mekanik juga dapat menolong menstabilkan hemodinamik dengan menurunkan penggunaan oksigen dari otot-otot respirasi.13
3. Untuk keseimbangan hemodinamik, sebaiknya ditunjang dengan resusitasi cairan. Cairan kristaloid seperti NaCl 0,9% atau Ringer Laktat sebaiknya diberikan per infus secara cepat 250-500 cc bolus dengan pengawasan yang cermat terhadap tekanan darah, akral, turgor kulit, dan urin output untuk menilai respon terhadap terapi.
4. Bila tekanan darah dan perfusi perifer tidak segera pulih, berikan obat-obat vasoaktif (adrenergik; agonis alfa yang indikasi kontra bila ada perdarahan seperti ruptur lien) :3,14,15
· Dopamin
Merupakan obat pilihan pertama. Pada dosis > 10 mcg/kg/menit, berefek serupa dengan norepinefrin. Jarang terjadi takikardi.
· Norepinefrin
Efektif jika dopamin tidak adekuat dalam menaikkan tekanan darah. Monitor terjadinya hipovolemi atau cardiac output yang rendah jika norepinefrin gagal dalam menaikkan tekanan darah secara adekuat. Pada pemberian subkutan, diserap tidak sempurna jadi sebaiknya diberikan per infus. Obat ini merupakan obat yang terbaik karena pengaruh vasokonstriksi perifernya lebih besar dari pengaruh terhadap jantung (palpitasi). Pemberian obat ini dihentikan bila tekanan darah sudah normal kembali. Awasi pemberian obat ini pada wanita hamil, karena dapat menimbulkan kontraksi otot-otot uterus.
· Epinefrin
Pada pemberian subkutan atau im, diserap dengan sempurna dan dimetabolisme cepat dalam badan. Efek vasokonstriksi perifer sama kuat dengan pengaruhnya terhadap jantung Sebelum pemberian obat ini harus diperhatikan dulu bahwa pasien tidak mengalami syok hipovolemik. Perlu diingat obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi perifer tidak boleh diberikan pada pasien syok neurogenik
· Dobutamin
Berguna jika tekanan darah rendah yang diakibatkan oleh menurunnya cardiac output. Dobutamin dapat menurunkan tekanan darah melalui vasodilatasi perifer.
| Obat | Dosis | Cardiac Output | Tekanan Darah | Resistensi Pembuluh Darah Sistemik |
| Dopamin | 2,5-20 mcg/kg/menit | + | + | + |
| Norepinefrin | 0,05-2 mcg/kg/menit | + | ++ | ++ |
| Epinefrin | 0,05-2 mcg/kg/menit | ++ | ++ | + |
| Fenilefrin | 2-10 mcg/kg/menit | - | ++ | ++ |
| Dobutamin | 2,5-10 mcg/kg/menit | + | +/- | - |
KESIMPULAN
Syok bukanlah merupakan suatu diagnosis. Syok merupakan sindrom klinis yang kompleks yang mencakup sekelompok keadaan dengan manifestasi hemodinamik yang bervariasi tetapi petunjuk yang umum adalah tidak memadainya perfusi jaringan. Syok neurogenik merupakan kegagalan pusat vasomotor sehingga terjadi hipotensi dan penimbunan darah pada pembuluh tampung (capacitance vessels).1,3
Penyebab syok neurogenik antara lain: Trauma medula spinalis dengan quadriplegia atau paraplegia (syok spinal), rangsangan hebat yang kurang menyenangkan seperti rasa nyeri hebat pada fraktur tulang, rangsangan pada medula spinalis seperti penggunaan obat anestesi spinal/lumbal, trauma kepala (terdapat gangguan pada pusat otonom), suhu lingkungan yang panas, terkejut, takut.3,4,5
Syok neurogenik termasuk syok distributif dimana penurunan perfusi jaringan dalam syok distributif merupakan hasil utama dari hipotensi arterial karena penurunan resistensi pembuluh darah sistemik (systemic vascular resistance). 11,16
Diagnosis syok kardiogenik Hampir sama dengan syok pada umumnya tetapi pada syok neurogenik terdapat tanda tekanan darah turun, nadi tidak bertambah cepat, bahkan dapat lebih lambat (bradikardi) kadang disertai dengan adanya defisit neurologis berupa quadriplegia atau paraplegia. 3,4,14,15
Konsep dasar untuk syok distributif adalah dengan pemberian vasoaktif seperti fenilefrin dan efedrin, untuk mengurangi daerah vaskuler dengan penyempitan sfingter prekapiler dan vena kapasitan untuk mendorong keluar darah yang berkumpul ditempat tersebut.4,9